Artikel ini adalah sebuah esai dasar. Artikel ini lebih panjang dari biasanya dan membahas lebih luas tentang masalah utama yang memengaruhi masyarakat.
Dalam sejarah budaya Eropa, perbandingan manusia dengan kera dan monyet telah direndahkan sejak awal.
Ketika Plato–dengan mengutip Heraclitus–menyatakan bahwa kera itu buruk dalam hubungannya dengan manusia dan manusia itu buruk dalam hubungannya dengan para dewa, ini sebenarnya penghinaan bagi kera. Hal ini secara transenden memutuskan hubungan mereka dengan manusia. Para Bapa Gereja berpikir lebih jauh lagi: Santo Gregorius dari Nazianzus dan Santo Isidore dari Sevilla membandingkan orang kafir dengan monyet.
Pada Abad Pertengahan, wacana Kristen mengakui simian sebagai sosok iblis dan perwakilan dari perilaku yang penuh nafsu dan dosa. Karena perempuan menjadi sasaran penghinaan yang serupa, segala sesuatunya berjalan seperti yang bisa diduga. Pada abad ke-11, Kardinal Peter Damian memberikan sebuah kisah tentang seekor monyet yang menjadi kekasih seorang bangsawan dari Liguria. Simian yang cemburu itu membunuh suaminya dan melahirkan anaknya.
Sarang monster
Beberapa abad kemudian pada tahun 1633, John Donne dalam karyanya “Metempsychosis” bahkan membiarkan salah satu anak perempuan Adam dirayu oleh seekor kera dalam sebuah perselingkuhan. Dengan penuh semangat dia menerimanya dan menjadi ketagihan.
Sejak saat itu, manifestasi seksis dari simianisasi terjalin erat dengan dimensi rasisnya. Jean Bodin, penemu teori kedaulatan, telah mengaitkan hubungan seksual antara hewan dan manusia dengan Afrika di selatan Sahara. Dia mencirikan wilayah tersebut sebagai sarang monster, yang muncul dari persatuan seksual antara manusia dan hewan.
Sejarah narasi oleh Antonio de Torquemada menunjukkan bagaimana dalam proses ini orang-orang Afrika menjadi iblis dan iblis-iblis itu menjadi rasial. Dalam versi pertama cerita ini (1570), seorang perempuan Portugis diasingkan ke Afrika lalu ia diperkosa oleh kera dan melahirkan bayinya.
Satu abad kemudian, kisah ini telah memasuki ranah pemikiran filosofis besar Eropa. John Locke dalam esainya pada tahun 1689 “Concerning Human Understanding”, menyatakan bahwa “perempuan telah mengandung dengan drills”. Para intelektual pada zamannya tahu betul bahwa panggung tempat terjadinya kisah cinta dan perkosaan yang melampaui batas ini adalah Afrika karena, menurut kearifan pada masa itu, drills hidup di Guinea.
Pada abad-abad berikutnya, simianisasi masuk ke dalam berbagai ilmu pengetahuan dan humaniora. Beberapa di antaranya adalah Antropologi, arkeologi, biologi, etnologi, geologi, kedokteran, filsafat dan, yang tak kalah penting, teologi.
Rasisme film ‘King Kong’
Sastra, seni, dan hiburan sehari-hari juga ikut menyoroti masalah ini. Film ini memopulerkan kombinasi representasi seksis dan rasis yang sangat menjijikkan. Puncaknya adalah film klasik yang sangat sukses dari pabrik horor Hollywood, “King Kong”.
Pada saat produksi King Kong, publik di Amerika Serikat (AS) terpaku pada sebuah percobaan perkosaan. Diceritakan tentang the Scottsboro Boys, sembilan remaja kulit hitam yang dituduh telah memerkosa dua orang perempuan kulit putih. Pada tahun 1935, sebuah cerita bergambar karya seniman Jepang Lin Shi Khan dan litografer Toni Perez diterbitkan. “Scottsboro Alabama” memiliki kata pengantar oleh Michael Gold, editor jurnal komunis New Masses.
Salah satu dari 56 gambar itu menampilkan kelompok pemuda yang dituduh dengan judul “Perkosaan Bersalah”. Sisa gambar lainnya dipenuhi dengan sosok simian hitam yang mengerikan yang memperlihatkan giginya dan menyeret seorang perempuan kulit putih yang tak berdaya.
Para seniman sepenuhnya memahami interaksi antara ideologi rasis, pemberitaan reaksioner, dan ketidakadilan di selatan. Mereka menyadari bahwa masyarakat kulit putih telah dikondisikan secara menyeluruh oleh kekerasan yang tidak manusiawi dari perbandingan hewan dan representasi simian, seperti dalam rasisme film “King Kong”.
Dilabeli dengan penyakit
Animalisasi dan bahkan bakterialisasi adalah elemen dehumanisasi rasis yang tersebar luas. Hal ini berkaitan erat dengan pelabelan orang lain dengan bahasa kontaminasi dan penyakit. Gambar-gambar yang menempatkan manusia sejajar dengan tikus yang membawa wabah penyakit merupakan bagian dari pengawalan ideologi rasisme anti-Yahudi dan anti-Cina.
Afrika dicap sebagai benua penular yang menginkubasi berbagai macam wabah penyakit di hutan-hutan yang panas dan lembab, yang disebarkan oleh orang-orang yang sembrono dan tidak terkendali secara seksual. AIDS secara khusus dikatakan berasal dari kecerobohan orang-orang Afrika dalam berhubungan dengan simian, yang mereka makan atau yang darahnya mereka gunakan sebagai obat perangsang.
Ini hanyalah bab terbaru dari deretan stereotip yang panjang dan buruk yang ditujukan kepada orang-orang yang berbeda seperti orang Irlandia atau orang Jepang, dan khususnya orang Afrika dan orang Afrika-Amerika. Melempar pisang di depan olahragawan kulit hitam merupakan provokasi rasis yang umum terjadi bahkan hingga saat ini.
Mengapa orang kulit hitam dilecehkan?
Apa yang menjelaskan asosiasi buruk terhadap orang kulit hitam yang difitnah sebagai simian ini? Kombinasi beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya:
Prevalensi berbagai jenis kera besar di Afrika, yang ukurannya paling mendekati manusia. Populasi kera besar di Asia lebih terbatas, sementara di Amerika kita dapat menemukan monyet, tetapi tidak ada kera;
Tingkat “jarak” estetika antara kulit putih dan kulit hitam, derajat yang lebih besar dari perspektif “keanehan” fisik orang kulit putih (tidak hanya berbeda dalam warna kulit dan tekstur rambut, tetapi juga fitur wajah) dibandingkan dengan ras “non-kulit putih” lainnya;
penghormatan yang lebih tinggi yang secara umum diberikan oleh orang Eropa kepada orang Asia dibandingkan dengan peradaban Afrika; dan
di atas semua itu, dampak psikis dari perbudakan rasial selama ratusan tahun di era modernitas, yang mencap “Negro” sebagai sub-manusia dan budak alami, dalam kesadaran global.
Perbudakan dalam skala besar membutuhkan pengurangan manusia menjadi objek. Justru karena itu, hal ini juga membutuhkan jenis dehumanisasi yang menyeluruh dan sistematis dalam teorisasi realitas tersebut.
Asal usul spesies
Jauh sebelum “rasisme ilmiah” pasca-Darwin mulai berkembang, orang dapat menemukan orang kulit hitam digambarkan lebih dekat dengan kera dalam Rantai Makhluk Besar.
Ambil contoh pertengahan abad ke-19 di Amerika, di mana poligenesis (asal-usul ras yang terpisah) dianggap serius. Ilmuwan terkemuka pada masa itu, Josiah C. Nott dan George R. Gliddon, dalam buku mereka yang berjudul “Types of Mankind” (1854), mendokumentasikan apa yang mereka anggap sebagai hierarki rasial yang obyektif dengan ilustrasi-ilustrasi yang membandingkan orang kulit hitam dengan simpanse, gorila, dan orangutan.
Seperti yang dikatakan oleh Stephen Jay Gould, buku tersebut bukanlah dokumen amatir, tetapi merupakan teks terkemuka di Amerika tentang perbedaan ras.
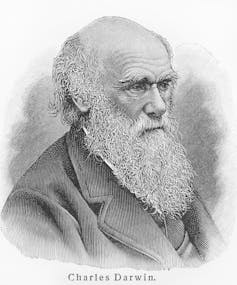
Karya revolusioner Darwin di 1859, On the Origin of Species, tidak mendiskreditkan rasisme ilmiah, melainkan hanya varian poligenetiknya. Darwinisme Sosial, yang menang secara monogenetik, akan menjadi ortodoksi rasial yang baru. Dominasi kulit putih secara global dianggap sebagai bukti keunggulan evolusi ras kulit putih.
Jika sekarang harus diakui bahwa kita semua berkerabat dengan kera, tetap saja dapat dikatakan bahwa konsanguitas orang kulit hitam jauh lebih dekat–mungkin sebuah identitas yang jelas.
Tarzan = kulit putih
Budaya populer memainkan peran penting dalam menyebarkan kepercayaan ini. Rata-rata orang awam Amerika tidak mungkin membaca jurnal ilmiah. Namun mereka pasti membaca H. Rider Haggard (penulis “King Solomon’s Mines” dan “She”) dan Edgar Rice Burroughs (pencipta “Tarzan”). Mereka pergi ke bioskop setiap minggu, termasuk genre “film rimba”. Mereka mengikuti strip komik harian seperti “The Phantom” - supercop kulit putih Afrika, Hantu yang berjalan.
Afrika dan orang Afrika menempati tempat khusus dalam khayalan kulit putih, dengan penggambaran yang paling memalukan. Burroughs akan menjadi salah satu penulis terlaris di abad ke-20. Tidak hanya dalam berbagai bukunya, tetapi juga dalam film yang dibuat dari buku-buku tersebut dan berbagai strip kartun dan spin-off komik, dari ciptaannya yang paling terkenal, “Tarzan” sebagai bagian dari Kera.
Tarzan memberikan citra yang tak terhapuskan dalam pikiran Barat tentang seorang pria kulit putih yang menguasai benua hitam. “Tar-zan” = “kulit putih” dalam bahasa Kera, demikian Burroughs yang merupakan seorang poliglot menginformasikan kepada kita. Ini adalah dunia di mana manusia berkulit hitam adalah binatang, simian, sementara kera yang sebenarnya adalah manusia.
Karya Burroughs termasuk karya yang berhasil, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sama sekali tidak biasa untuk periode tersebut. Sebaliknya, karya ini mengonsolidasikan ikonografi Manichean yang tersebar di seluruh dunia Barat pada paruh pertama abad ke-20 dan bertahan hingga saat ini. Dalam konflik antara terang dan gelap ini, orang Eropa berkulit putih menguasai orang kulit hitam yang mereka anggap lebih rendah.
Pengumuman Lumumba
Seri kartun “Tintin” karya kartunis Belgia Hergé, misalnya, termasuk buku “Tintin au Congo” yang terkenal, juga menggambarkan orang Afrika sebagai makhluk yang lebih rendah.
Tidak mengherankan, macaques (monyet) menjadi salah satu istilah rasis yang digunakan oleh orang kulit putih di Kongo Belgia untuk orang kulit hitam, seperti halnya “macacos” di Afrika Portugis. Dalam pidato Hari Kemerdekaan tahun 1960, pemimpin Kongo Patrice Lumumba mengecam warisan kolonialisme Belgia yang menindas (yang membuat heran dan marah raja Belgia dan para pembesarnya, yang mengharapkan penghormatan dari penduduk asli). Dia menyimpulkan:
Nous ne sommes plus vos macaques! (Kami bukan lagi monyet-monyet kalian)
Kisah ini tampaknya disembunyikan–tidak ada dokumentasi yang ditemukan untuk itu–tetapi peredarannya yang luas membuktikan aspirasi dekolonial jutaan orang Afrika. Sayangnya, dalam waktu kurang dari satu tahun, Lumumba mati, dibunuh dengan persekongkolan agen-agen Barat, dan negara itu beralih ke pemerintahan neokolonial.
Aliansi lintas kelas yang rasis
Penggunaan simianisasi sebagai penghinaan rasis terhadap orang kulit hitam belum berakhir, seperti yang ditunjukkan oleh kehebohan di Afrika Selatan yang dipicu oleh Penny Sparrow, seorang perempuan kulit putih, yang mengeluh tentang orang-orang kulit hitam yang berpesta pora di malam Tahun Baru:
Mulai sekarang saya akan menyebut orang kulit hitam di Afrika Selatan sebagai monyet karena saya melihat monyet-monyet kecil yang lucu melakukan hal yang sama, memungut dan membuang sampah sembarangan.
Amarah publik yang dipantik Sparrow menunjukkan betapa dalamnya prasangka dan stereotip rasial.

Hal ini tidak berhenti pada batas-batas kelas. Internet telah dipenuhi dengan perbandingan kera sejak Barack Obama dan Michelle Obama pindah ke Gedung Putih. Bahkan sebuah surat kabar sosial-liberal, seperti De Morgen dari Belgia, menganggap lucu untuk melakukan simianisasi terhadap Sang Presiden dan First Lady tersebut.
Aliansi lintas kelas untuk melawan orang lain yang tidak berkelas adalah ciri khas rasisme.
Theodore W. Allen pernah mendefinisikannya sebagai “kematian sosial dari penindasan rasial”:
… reduksi semua anggota kelompok yang tertindas menjadi satu status sosial yang tidak terdiferensiasi, di bawah status sosial anggota kelompok penindas.
Animalisasi tetap menjadi instrumen yang jahat dan efektif dalam bentuk desosialisasi dan dehumanisasi. Simianisasi adalah versi dari strategi ini, yang secara historis merupakan kombinasi mematikan dari seksisme dan rasisme.
Bersama Silvia Sebastiani, Wulf D. Hund dan Charles W. Mills menyunting satu volume Buku Tahunan Analisis Rasisme tentang “Simianisasi. Kera, Gender, Kelas, dan Ras”. Zürich, Berlin, Wien, Münster: Lit 2015/16 (ISBN 978-3-643-90716-5).
Charles Mills meninggal dunia pada 2021. Obituari dan informasi lebih lanjut tentang filsuf yang telah berpulang ini dapat ditemukan di sini:
Rahma Sekar Andini dari Universitas Negeri Malang menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris


